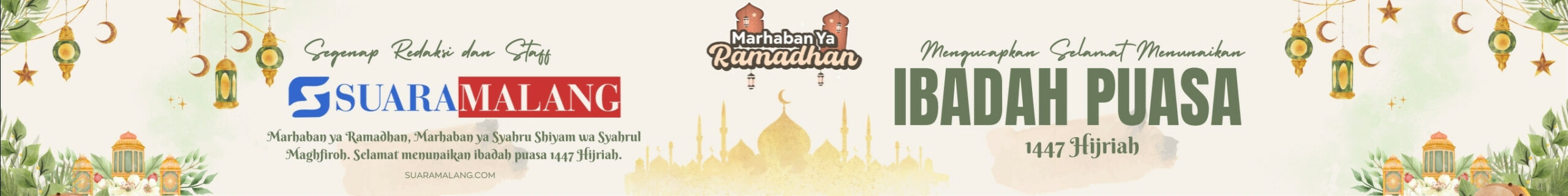SUARAMALANG.COM, Jakarta – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibentuk sejak tahun 2014 sebagai amanat Undang‑Undang No. 28 tentang Hak Cipta, dengan mandat utama untuk menghimpun royalti dari pemanfaatan musik secara komersial dan mendistribusikannya kepada para pencipta lagu melalui lembaga-lembaga manajemen kolektif (LMK). Namun setelah lebih dari satu dekade berdiri, lembaga ini justru menampilkan wajah yang buram ketika publik mencoba menelisik ke dalam dapurnya.
Hingga awal Agustus 2025, halaman resmi finance-statement di situs https://www.lmkn.id/finance-statement/ yang seharusnya memuat laporan keuangan secara terbuka kepada publik, tampak kosong melompong. Tak satu pun dokumen yang dapat diakses publik secara digital. Tidak ada neraca, tidak ada laporan distribusi, tidak ada rincian potongan, bahkan tidak ada penjelasan mengenai dana yang telah dihimpun dan disalurkan. Hanya tersedia menu halaman statis, tanpa satu pun tautan aktif ke dokumen akuntabilitas finansial.
Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, LMKN diwajibkan menjalankan pengelolaan secara transparan, proporsional, dan akuntabel. Lebih jauh, Pasal 17 dari PP tersebut menekankan bahwa informasi pengelolaan royalti wajib dilaporkan kepada masyarakat, terutama para pemilik hak. Ketika transparansi tak dijalankan, kepercayaan ikut dipertaruhkan.
Ketua LMKN Dharma Oratmangun dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa lembaganya telah menyampaikan laporan keuangan melalui media cetak dan siap menanggapi permintaan data secara langsung. Namun dalam era digital dan keterbukaan informasi, absennya laporan keuangan yang dapat diakses publik di situs resmi menjadi tanda tanya besar: mengapa lembaga publik yang menghimpun miliaran rupiah dana kolektif bersikap seolah tak ingin diaudit masyarakat?
Masalah transparansi ini muncul di tengah kisruh terbaru seputar kebijakan royalti yang dinilai memberatkan pelaku usaha kecil, terutama kafe dan restoran. LMKN diketahui menggunakan sistem tarif berdasarkan jumlah kursi, bukan hanya jenis usaha. Sebuah kafe dengan 30 kursi, misalnya, bisa dikenai royalti tetap tahunan hanya karena pengunjungnya berpotensi mendengar lagu yang diputar, meski tidak semua lagu itu berizin atau digunakan secara aktif.
Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha merasa sistem ini tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan intensitas pemutaran. Bahkan, dalam beberapa kasus, usaha yang hanya memutar radio atau lagu streaming tanpa niat komersial khusus tetap dipungut iuran lisensi. “Ini seperti dipaksa bayar listrik padahal kita hidup di tenda dan cuma nyalakan lilin,” sindir salah satu pemilik kedai kopi kecil di Yogyakarta, yang enggan disebutkan namanya.
Mekanisme penarifan ini tidak hanya menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha, tetapi juga memantik pertanyaan baru dari kalangan pencipta lagu. Beberapa asosiasi pencipta menuntut adanya sistem pelacakan lagu berbasis digital — semacam music tracking system — yang mampu mencatat lagu apa yang benar-benar diputar di lokasi tertentu, agar distribusi royalti tidak hanya berdasarkan jumlah dana, tetapi juga keterpakaiannya.
Sayangnya, ketika ditelusuri lebih lanjut, laman finance-statement yang diharapkan memuat informasi pendistribusian tersebut justru nihil konten. Tidak ada pelaporan digital yang menunjukkan lagu siapa yang telah digunakan, berapa banyak, dan kepada siapa dana disalurkan. Sistem Velodiva yang digembar-gemborkan sebelumnya sebagai platform pelacakan pun belum terintegrasi secara publik.
Sementara itu, LMKN mencatat peningkatan pendapatan royalti dari Rp35 miliar di tahun 2022 menjadi Rp55 miliar di 2023. Namun, bagaimana dana tersebut digunakan dan kepada siapa dibagikan, masih menjadi teka-teki yang tidak dapat dijawab dari situs resmi lembaga.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Januari 2024 pernah mewanti-wanti LMKN untuk segera membenahi sistem transparansinya. “Keterbukaan informasi menjadi kunci kepercayaan publik,” tegasnya kala itu. Namun hingga hari ini, seruan tersebut belum direspons dalam bentuk yang konkret.
Di tengah arus digitalisasi dan tuntutan akuntabilitas publik, LMKN justru tampak gagap menghadirkan keterbukaan data. Royalti terus ditarik dari usaha kecil hingga konglomerasi, tetapi laporan ke mana dana itu mengalir tetap berada di balik tirai. Pertanyaan yang kini menggema: siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang hanya dimanfaatkan?
Pewarta : M.Nur