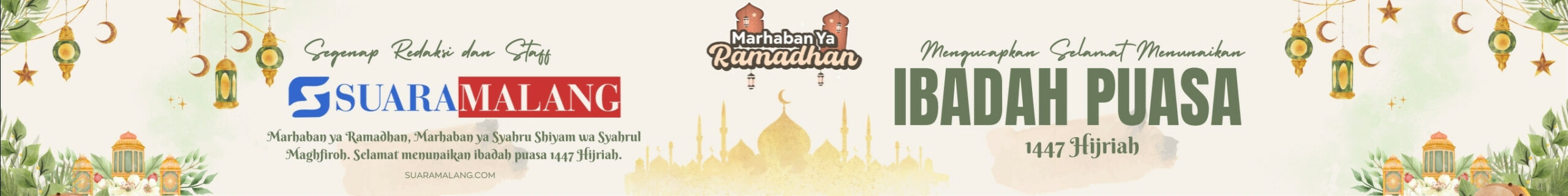SUARAMALANG.COM, Jakarta – Seberapa serius Indonesia dalam memulihkan uang rakyat yang hilang akibat korupsi? Pertanyaan ini kembali mengemuka setelah berbagai data terbaru menunjukkan jurang yang menganga lebar: nilai kerugian negara yang fantastis versus pengembalian yang relatif kecil.
Kerugian Ratusan Triliun, Pengembalian Hanya Beberapa Persen
Laporan resmi menunjukkan, sepanjang 2024 kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai sekitar Rp45,7 triliun. Angka ini bukan perkiraan liar, melainkan data yang disampaikan dalam laporan tahunan penegak hukum dan audit negara.
Namun, jumlah uang yang berhasil kembali ke kas negara ternyata hanya secuil jika dibandingkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode 2020–2024 melaporkan pengembalian aset senilai Rp2,544 triliun. Khusus untuk tahun 2024, angka itu hanya Rp731,5 miliar.
Sementara itu, Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset mencatat pengembalian sekitar Rp1,32 triliun pada 2024, ditambah Rp600 miliar hingga Mei 2025. Bahkan di awal 2025, KPK baru mampu menyetor Rp53 miliar dari lelang barang rampasan.
Jika dihitung kasar, total pengembalian aset tidak sampai 6 persen dari kerugian yang dilaporkan. Sisanya—puluhan triliun rupiah—masih misterius. Ke mana larinya uang rakyat itu?
Mengapa Gap Ini Terjadi?
Pengembalian aset korupsi bukan perkara mudah. Sejumlah pakar menyebut ada tiga faktor utama:
Aset yang disembunyikan – Pelaku korupsi sering memecah aset ke banyak rekening, perusahaan cangkang, atau menempatkannya di luar negeri. Pelacakan menjadi sulit dan memakan waktu.
Keterbatasan hukum – Indonesia masih mengandalkan mekanisme berbasis vonis (conviction-based). Artinya, aset baru bisa dirampas setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan banyak negara maju yang sudah menerapkan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, di mana aset bisa disita lebih cepat.
Proses birokrasi dan administrasi – Pemulihan aset melewati banyak tahapan: pembekuan, penilaian, lelang, hingga penyetoran ke kas negara. Sering kali nilai menyusut karena biaya administrasi, depresiasi aset, atau kerusakan.
RUU Perampasan Aset: Harapan Baru atau Sekadar Wacana?
Situasi ini memunculkan desakan untuk mempercepat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini diharapkan memberi dasar hukum lebih kuat bagi penyitaan aset hasil korupsi, termasuk tanpa menunggu putusan pengadilan.
“Menempatkan RUU Perampasan Aset di posisi lima besar menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini memahami urgensi instrumen ini dalam memberantas korupsi. Ini bukan hanya simbolis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum kita,” ujar Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
RUU ini juga diharapkan memberi ruang pembentukan pengadilan khusus aset dan memperkuat peran lembaga seperti Badan Pemulihan Aset (BPA) yang baru dibentuk di Kejaksaan Agung. Dengan mandat yang lebih luas, BPA kini bahkan bisa bekerja sama lintas negara dan mengelola aset yang disita hingga ke tingkat kejaksaan negeri.
Kasus Nyata: Potret Kesenjangan
Beberapa kasus menjadi contoh betapa besar potensi kerugian dibanding hasil pemulihan. Dalam perkara dugaan korupsi di PGN/IAE, KPK mengungkap indikasi kerugian sekitar USD15 juta, tetapi baru USD1 juta yang berhasil diamankan.
Belum lagi kasus besar seperti dugaan korupsi di tubuh Pertamina yang mencuat 2025, dengan estimasi kerugian mencapai Rp193,7 triliun. Bayangkan jika pola pengembalian hanya beberapa persen, maka uang rakyat yang kembali bisa nyaris tak berarti.
Dampak ke Publik dan Kredibilitas Negara
Jurang besar antara kerugian dan pengembalian memunculkan kegelisahan publik. Di media sosial, seruan seperti “Jangan cuma tangkap orangnya, kembalikan uangnya!” kerap trending setiap kali ada operasi tangkap tangan.
Secara fiskal, kerugian ini bukan sekadar angka. Uang yang lenyap seharusnya bisa membiayai sekolah gratis, membangun rumah sakit, hingga memperbaiki infrastruktur. Semakin kecil aset yang kembali, semakin besar pula beban APBN.
Tak heran jika sebagian kalangan menilai penegakan hukum akan dianggap setengah hati bila pemulihan aset tidak jadi prioritas. Penangkapan pelaku tanpa pengembalian uang negara hanya menyentuh permukaan masalah.
Solusi dan Jalan ke Depan
Ada beberapa langkah strategis yang bisa memperkecil gap ini:
Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, dengan model yang adaptif dan kompatibel dengan standar internasional.
Pemanfaatan teknologi pelacakan dan intelijen keuangan, termasuk kerja sama dengan lembaga internasional untuk memburu aset di luar negeri.
Transparansi dan akuntabilitas, misalnya laporan publik rutin soal jumlah aset yang ditemukan, status lelang, dan hasil penyetoran ke kas negara.
Sinergi antar lembaga – KPK, Kejaksaan, PPATK, BPK, hingga Polri harus bergerak bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Disparitas antara kerugian negara dan pengembalian aset korupsi bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin dari seberapa serius negara memerangi korupsi dan melindungi uang rakyat. Selama gap ini masih lebar, publik akan terus bertanya-tanya: siapa yang benar-benar diuntungkan dari korupsi? Pelaku yang dipenjara, atau sistem yang membiarkannya?
Pewarta : M.Nur